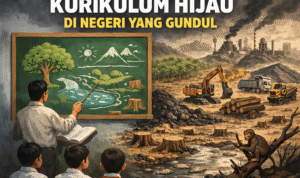Oleh Umar Robbani (Jurnalis)
Menteri Sosial Saifullah Yusuf telah menyerahkan 40 nama usulan untuk menjadi pahlawan nasional kepada Kementerian Kebudayaan beberapa waktu lalu. Salah satu nama yang ramai menjadi sorotan publik adalah Presiden RI ke-2, Soeharto. Meski belum dipublis secara resmi, namun Gus Ipul telah mengakui ada nama Soeharto di antara 40 nama yang diajukan.
Usulan ini mendapatkan banyak respon negatif khusus dari kalangan aktivis kelompok masyarakat sipil. Dk kalangan aktivis, Soeharto memiliki wajah diktator dan korup. Dia menduduki jabatan presiden selama 32 tahun sejak 1967. Selama dia menjabat banyak terjadi peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang sampai saat ini tidak pernah dituntaskan secara hukum. Jadi wajar jika banyak kelompok yang selama ini aktif bersuara soal keadilan HAM menolak usulan tersebut.
Menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional merupakan bentuk penghianatan terhadap cita-cita reformasi. Hal itu sama saja dengan menganggap pelanggaran HAM dan korupsi sebagai sebuah tindakan yang wajar. Sebab ada pelakunya ditasbihkan sebagai pahlawan.
Tapi kenapa pemerintah ngotot ingin memberikan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto? Bahkan wacana tersebut beberapa kali muncul tapi belum kesampaian, setidaknya sebelum Gus Ipul jadi Menteri Sosial.
Dalang Undang-undang PMA
Setelah menerima mandat mengganti Ir Soekarno melalui Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada 1966, Soeharto akhirnya ditunjuk sebagai pejabat presiden oleh MPR sampai terpilihnya presiden di tahun 1967. Baru pada 1968 melalui sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), Soeharto terpilih sebagai Presiden RI ke-2.
Pada awal kepemimpinannya di 1967, sebelum terpilih secara resmi, Pemerintah Indonesia menerbitkan menerbitkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing (PMA). Undang-undang ini yang menjadi pembuka keran investasi asing ke Indonesia. Padahal pada Orde Lama, Soekarno sangat anti asing terlebih terhadap negara-negara barat.
Tidak lama dari diterbitkannya UU PMA, masih di tahun yang sama pada 5 April, untuk pertama kalinya Pemerintah Indonesia melakukan penandatanganan kontrak karya Penanaman Modal Asing. Kontrak karya itu dilakukan antara pemerintah dengan Freeport Sulphur Company atau PT Freeport Indonesia milik Amerika. Perusahaan itu masih terus beroperasi hingga sekarang di tengah kemiskinan dan kerusakan lingkungan di Papua.
Mulai dari tahun tersebut, investor asing (mayoritas Amerika) terus berdatangan menjarah kekayaan alam Indonesia dengan modus investasi. Kerusakan alam dimana-mana, tapi tingkat kemiskinan masyarakat malah meningkat.
Tak hanya UU PMA, masih di 1967 pemerintahan Soeharto juga menerbitkan UU No. 11 Tahun 1967 yang berisi tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Melalui UU itu negara diberikan hak mutlak untuk memberikan ijin dalam melakukan ekstraksi terhadap semua sumber daya mineral kepada individu maupun perusahaan.
Pelanggaran HAM Selama Orde Baru
Mengutip kompas.com, berdasarkan catatan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) setidaknya ada 10 kasus dugaan pelanggaran HAM yang diduga dilakukan Soeharto selama berkuasa.
1. Kasus Pulau Buru 1965-1966
Dalam peristiwa kejahatan kemanusiaan di Pulau Buru terjadi Soeharto merupakan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban atau Pangkoops Pemulihan Kamtub.
Melalui keputusan Presiden Nomor 179/KOTI/65, secara resmi berdiri Komando Operasi Pemulihan Kemanan dan Ketertiban (KOPKAMTIB) dan Soeharto menjadi Panglima. Soeharto diduga telah menyebabkan ribuan orang menjadi korban pembunuhan, penangkapan, penahanan massal dan pembuangan ke pulau Buru.
2. Penembakan misterius (Petrus) 1981-1985
Penembakan Misterius atau lebih tenar dengan sebutan Petrus merupakan tindakan hukuman mati pemerintah Soeharto. Targetnya adalah residivis, bromocorah, preman, bahkan sekadar orang bertato. Mereka ditembak mati tanpa pengadilan. Peristiwa itu terjadi sepanjang 1981-1985.
Amnesty Internasional dalam laporannya mencatat korban jiwa karena kebijakan tersebut mencapai kurang lebih sekitar 5.000 orang, tersebar di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Bandung.
3. Tanjung Priok 1984-1987
Peristiwa Tanjung Priok adalah kerusuhan akibat pembatasan pemerintah melalui Babinsa terhadap kegiatan keagamaan. Sebab kegiatan pengajian atau ceramah kerap diisi kritik terhadap pemerintah. Ini adalah dampak dari kebijakan asas tunggal Pancasila yang dilakukan secara represif oleh Soeharto.
Puncaknya ketika terdapat pemaksaan penurunan banner pengajian oleh Babinsa pada salah satu masjid. Tindakan itu mendapatkan perlawanan dari masyarakat dan terjadi kerusuhan yang diwarnai dengan kekerasan dari tentara.
Dalam peristiwa itu Soeharto dianggap menggunakan KOPKAMTIB sebagai instrumen penting mendukung dan melindungi kebijakan politiknya. Akibat dari kebijakan ini, dalam Peristiwa Tanjung Priok 1984, sekitar lebih 24 orang meninggal, 36 terluka berat, 19 luka ringan.
4. Tragedi Talangsari 1984-1987
Dampak peneraman asas tunggal Pancasila di masa Orde Baru juga turut menjadi pemicu terjadinya Tragedi Talangsari. Peristiwa Talangsari adalah kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi pada 7 Februari 1989 di Dusun Talangsari III, Kabupaten Lampung Timur.
Hasil penyelidikan pro justisia Komnas HAM (2006) menyebutkan adanya dugaan pelanggaran HAM berat dalam peristiwa Talangsari, berupa Pembunuhan terhadap 130 orang, Pengusiran Penduduk secara Paksa 77 orang, Perampasan Kemerdekaan 53 orang, Penyiksaan 46 orang, dan Penganiayaan atau Persekusi sekurang-kurangnya berjumlah 229 orang.
5. Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh (1989-1998)
Pemberlakukan operasi ini adalah kebijakan yang diputuskan secara internal oleh ABRI setelah mendapat persetujuan dari Presiden Soeharto.
Berdasarkan hasil investigasi Komnas HAM, dalam kurun waktu sepuluh tahun berlangsungnya operasi militer telah menyebabkan sedikitnya 781 orang tewas, 163 orang hilang, 368 orang mengalami penyiksaan/penganiayaan dan 102 perempuan mengalami pemerkosaan.
6. DOM Papua (1963-2003)
Pemberlakuan ini dimaksudkan untuk mematahkan perlawanan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Kebijakan ini mengakibatkan terjadinya berbagai peristiwa seperti Teminabun 1966-1967, sekitar 500 orang ditahan dan kemudian dinyatakan hilang, Peristiwa Kebar 1965 dengan 23 orang terbunuh, Peristiwa Manokwari 1965 dengan 64 orang dieksekusi mati, peristiwa Sentani dengan 20 orang menjadi korban penghilangan paksa, Enatorali 1969-1970, 634 orang terbunuh.
Sementara Peristiwa Jayawijaya dan Wamena Barat, melalui Operasi Tumpas pada kurun waktu 1970-1985 terjadi pembantaian di 17 desa.
7. Peristiwa 27 Juli 1996
Dalam Peristiwa 27 Juli, Soeharto memandang Megawati sebagai ancaman terhadap kekuasaan politik Orde Baru. Soeharto hanya menerima Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI pimpinan Suryadi yang menjadi lawan politik PDI pimpinan Megawati.
Aksi kekerasan yang diduga berupa pembunuhan, penangkapan dan penahanan dilakukan terhadap para simpatisan PDI pimpinan Megawati. Baca juga: OJK Pastikan Pindar Dana Syariah Indonesia Bayar Kerugian Lender dari Aset Dalam peristiwa ini, 11 orang meninggal, 149 luka-luka, 23 orang hilang, 124 orang ditahan.
8. Penculikan dan Penghilangan Secara Paksa 1997–1998
Peristiwa ini terjadi tidak terlepas dari konteks politik peristiwa 27 Juli, yakni menjelang Pemilihan Umum 1997 dan Sidang Umum MPR 1998. Selama masa inisetidaknya ada 23 aktivis pro demokrasi dan masyarakat yang dianggap akan bergerak melakukan penurunan Soeharto menjadi korban penculikan dan penghilangan paksa.
Komando Pasukan Khusus, (Kopassus) disebut menjadi eksekutor lapangan, dengan nama operasi “Tim Mawar”. Baca juga: Dalam Sidang, Eks Dirut PGN Bantah Terima Suap di Kasus Jual Beli Gas Sebanyak 9 orang dikembalikan, 1 orang meninggal dunia dan 13 orang masih hilang (“Laporan Hasil Penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa Penghilangan Paksa”, 2006).
9. Peristiwa Trisakti 12 Mei 1998
Peristiwa Trisakti 1998, terjadi pada 12 Mei 1998. Saat itu aktivis dan mahasiswa pro demokrasi mendorong reformasi total dan turunnya Soeharto dari jabatannya karena krisis ekonomi dan maraknya korupsi kolusi dan nepotisme (KKN).
Tindakan represif penguasa melalui ABRI menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan luka-luka. Empat orang mahasiswa Universitas Trisakti tewas tertembak peluru aparat keamanan.
10. Peristiwa 13-15 Mei 1998
Peristiwa 13–15 Mei 1998 merupakan rangkaian dari kekerasan yang terjadi dalam peristiwa Trisakti, penculikan dan penghilangan paksa.
Ketidakberdayaan pemerintahan Soeharto mengendalikan tuntutan mahasiswa dan masyarakat, direspons dengan sebuah “pembiaran” kekerasan dan kerusuhan pada 13-15 Mei 1998. Dalam peristiwa ini terjadi pembunuhan, penganiayaan, perusakan, pembakaran, penjarahan, penghilangan paksa, perkosaan, serta penyerangan terhadap etnis tertentu.
Kelayakan Soeharto Menyandang Gelar Pahlawan
Rentetan dosa Soeharto itu belum termasuk pemberedelan media massa seperti yang dialami oleh Majalah Tempo, Harian Sinar Harapan, dan Harian Indonesia Raya. Bahkan mungkin saja lebih dari itu. Ditambah lagi Soeharto juga masuk dalam jajaran presiden paling korup sepanjang masa yang dibuat oleh Transparency International melalui Laporan Korupsi Global 2004 via Forbes.
Di era digital saat ini, tidak sulit untuk mencari referensi latar belakang Soeharto, baik yang berbentuk buku ataupun artikel online. Nyaris tidak ada pemberitaan atau informasi yang positif terhadap dirinya. Informasi-informasi yang ada saat ini seharusnya cukup untuk menimbang apakah jenderal bintang lima itu layak menjadi pahlawan nasional.
Lalu, kenapa Soeharto layak jadi Pahlawan Nasional? Kenapa Gus Ipul?!