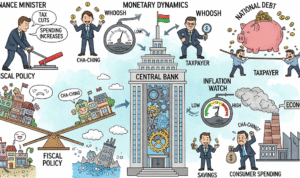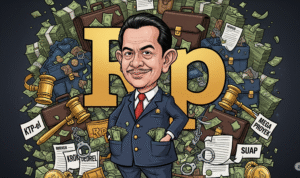Yasir A. Rapat, S.H. Advokat Muda Lampung Barat
Setiap awal tahun anggaran, desa-desa di Indonesia memasuki masa paling rawan dalam tata kelola pemerintahan. Musyawarah pekon digelar, aspirasi warga mengalir deras, dan daftar kebutuhan pembangunan membengkak. Jalan rusak, drainase mampet, jembatan tua—semuanya mendesak. Satu masalah yang selalu sama: uangnya tidak cukup.
Di titik inilah Kepala Desa berdiri di persimpangan berbahaya. Ia dituntut peka terhadap kebutuhan masyarakat, tetapi dibatasi oleh regulasi dan kemampuan fiskal desa. Ketika anggaran tidak mampu menutup semua kebutuhan, swadaya masyarakat sering dipilih sebagai jalan tengah. Namun, solusi sosial ini kerap berubah menjadi bumerang hukum.
Kasus-kasus yang muncul di Kabupaten Tanggamus memberi pelajaran mahal: banyak Kepala Desa akhirnya berhadapan dengan aparat penegak hukum bukan karena niat memperkaya diri, melainkan karena kekacauan administrasi dan miskinnya pendampingan hukum sejak awal. Kebijakan yang lahir dari itikad baik justru ditafsirkan sebagai pelanggaran.
Masalahnya bukan semata pada individu Kepala Desa, melainkan pada sistem yang membiarkan mereka berjalan sendirian di labirin regulasi.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menempatkan Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Kekuasaan ini di atas kertas terlihat besar, tetapi dalam praktik sering berubah menjadi beban hukum yang menakutkan. Setiap kesalahan prosedur—bahkan yang bersifat administratif—berpotensi diseret ke ranah pidana.
Di sinilah logika penegakan hukum kita kerap terbalik. Dalam hukum administrasi negara, pidana adalah ultimum remedium, jalan terakhir. Seharusnya, kesalahan administratif dibina, dikoreksi, dan diperbaiki. Namun yang kerap terjadi justru sebaliknya: pidana dijadikan pintu masuk pertama. Kepala Desa langsung duduk di kursi pesakitan, sementara akar masalah—ketidakcakapan sistem pendampingan—luput dibenahi.
Ironisnya, kesadaran akan pentingnya pendampingan hukum sering datang terlambat. Banyak Kepala Desa baru mencari advokat ketika surat panggilan sudah tiba. Pada tahap itu, hukum tidak lagi bersifat preventif, melainkan represif. Negara hadir bukan sebagai pembina, melainkan penghukum.
Situasi ini berbahaya. Kepala Desa yang terus-menerus hidup dalam bayang-bayang kriminalisasi akan memilih jalan aman: tidak berani mengambil keputusan, tidak berani berinovasi, dan lebih sibuk menyelamatkan diri daripada membangun desa. Pembangunan pun berjalan tersendat, sementara masyarakat kembali menjadi korban.
Karena itu, pendampingan hukum harus diposisikan sebagai kebutuhan dasar dalam tata kelola desa, bukan sebagai layanan mewah atau reaksi darurat. Pendampingan sejak tahap perencanaan dan penganggaran akan membantu memastikan setiap kebijakan desa memiliki dasar hukum yang jelas, tertib administrasi, dan terlindungi secara yuridis.
Lebih dari sekadar melindungi Kepala Desa, pendampingan hukum juga menjaga rasionalitas penegakan hukum itu sendiri. Tidak semua kesalahan adalah kejahatan. Tidak setiap kekeliruan administratif layak dibayar dengan pidana.
Belajar dari Tanggamus, kita perlu bertanya lebih jauh: apakah negara benar-benar ingin membangun desa, atau sekadar menunggu kesalahan untuk menghukum? Jika desa diposisikan sebagai ujung tombak pembangunan, maka Kepala Desa seharusnya diperkuat kapasitas dan perlindungan hukumnya, bukan dibiarkan sendirian menghadapi risiko.
Pendampingan hukum bukan tameng untuk menutupi korupsi. Ia justru pagar agar kekuasaan desa tidak tergelincir ke arah yang salah. Tanpa itu, desa akan terus menjadi ladang empuk kriminalisasi, dan pembangunan hanya tinggal jargon.
Dan pada akhirnya, yang kita bangun bukan desa yang berdaya, melainkan desa yang takut.(**)